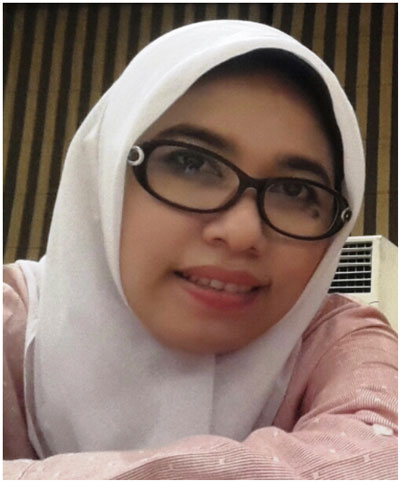Oleh: Kamilia Hamidah*
Lima belas Maret 2019, Jumat yang penuh berkah itu terlukai dengan tragedi penembakan massal terjadi di masjid An-Nuur dan masjid Linwood, di Christchurch, New Zealand. Hingga hari ini media masih dipenuhi dengan berbagai kecaman dan hujatan yang mengutuk keras aksi tersebut. Tercatat peristiwa tersebut telah menewaskan 49 korban, 48 luka-luka, 39 dilarikan ke rumah sakit, dan 11 orang lainnya menjalani perawatan insentif.
Seorang pemuda berkewarganegaraan Australia, Brenton Harrison Tarrant (28 tahun), juga seorang ultra nasionalis, dengan biadabnya memposting rekaman penembakan tersebut dan menyebarkannya dari laman sosial medianya. Ia juga memposting 87 halaman manifesto sebelum melakukan aksi brutalnya, manifesto yang penuh dengan sentimen anti-imigran dan juga anti-Muslim.
Peristiwa tersebut meskipun dengan cepat pelaku dapat segera dibekuk aparat keamanan setempat, tetapi gestur pelaku sama sekali tidak memunculkan rasa penyesalan atas tindakannya, bahkan semakin menunjukkan sebentuk aklamasi kebencian. Rekaman beberapa menit aksi penembakan brutal tersebut sempat menjadi konsumsi publik dan menjadi viral di sosial media.
Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Arden, dalam keterangan pers-nya menggambarkan penyerangan itu sebagai “aksi kejahatan yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya”, dan berjanji untuk mengubah peraturan kepemilikan senjata. Kepada wartawan ia berkata: Saya katakan satu hal saat ini, bahwa aturan kepemilikan senjata akan berubah, saatnya akan berubah.
Ada tiga hal yang mungkin dapat kita telaah bersama dari tragedi ini. Pertama, identitas dan ancaman marginalisasi, kedua, kebencian, dan ketiga media sebagai bagian dari saluran penyebar kebencian itu sendiri. Dalam konteks global, kita dihadapkan pada kenyataan global village, di mana di satu sisi sentimen ‘negara bangsa’ mengalami kemunduran yang ditandai dengan semakin tingginya interdependensi antarnegara, sehingga menjadikan dunia sebagai desa global. The world had grown global.
Namun, sebuah artikel Why a Nation Needs National Story yang beberapa waktu lalu terbit di Foreign Affairs menjadi sebuah ungkapan kegundahan pada negara-negara yang menghadapi massifnya arus imigrasi, baik secara temporal maupun permanen. Komposisi masyarakat yang sangat beragam di mana memungkinkan seseorang untuk berbaur dengan orang lain dengan berbagai latar belakang, baik itu kultur, budaya atau agama.
Di sisi lain, kemajuan perkembangan teknologi dan informasi menjadikan seseorang tetap merasa sebagai bagian dari identitas kulturalnya, meskipun mereka tinggal di negara lain dengan berbeda kultur. Dengan demikian, para pendatang imigran ini mampu menjaga dan mempertahankan tradisi dan identitas kulturalnya, senantiasa dapat terhubung dengan teman atau kolega yang mempunyai kedekatan secara identitas.
Namun, konektifitas bukannya semakin menjadikan seseorang mendapatkan koneksi dengan orang yang berbeda dari latar belakang yang beragam, justru makin mengkotak-kotakkan seseorang terbatas pada seberapa seringnya interaksi terjadi dengan komunitasnya sendiri. Maka terjadilah ada yang disebut being native in an alien nation, merasa origin meskipun dalam negara yang berbeda. Sentimen kebangsaan pada negara tujuan itu akan tetap dangkal karena tidak ditopang dengan interaksi interkultural yang memungkinkan semua sub-national bisa dengan totalitas berinteraksi dalam aktivitas sosialnya maupun aktifitas rutinnya.
Di sisi lain, dengan dalih modernitas, global ekonomi plus kemungkinan pada terbukanya koalisi transnasional, memaksa para elite negara untuk membuat reformasi besar-besaran pada ranah global. Sehingga secara tidak langsung membawa dampak munculnya identitas supranasional, yang di sisi lain memaksa pada terpinggirkannya identitas nasional yang selama ini telah menjadi bagian dari masyarakat.
Mungkin pada satu sisi akan menumbuhkan terciptanya kebersamaan dan toleransi beragama dan berbudaya, akan tetapi di sisi lain, pada kasus di mana tidak terakomodirnya sentimen identitas secara proporsional, maka hal itu akan menjelma menjadi penyakit laten yang bahkan lebih sadis dari teroris mana pun. Sebut saja sebagian telah menyebut fenomena ultra national white supremacist ini sebagai “White ISIS”.
Fukuyama dalam sebuah artikelnya Against Identity Politics, menekankan orang tidak akan pernah berhenti memikirkan diri mereka sendiri dan masyarakat mereka secara identitas. Identitas seseorang tidak pasti atau tidak harus dilahirkan, identitas mana yang dominan tergantung pada sejauh mana konteks sosial semakin memperkuat sentimen tersebut. Sehingga ketika identitas ‘merasa’ termarginalkan atau ‘merasa’ terancam akan dapat digunakan kelompok ultra oportunis untuk semakin memperlebar sekat ‘kita dan mereka’ dan semakin memperluas budaya kebencian.
Budaya kebencian akan mengejala dan menjadi penyakit sosial yang akan memenuhi ruang publik, mencabik-cabik ketahanan sosial suatu masyarakat. Tanpa menyebutkan nama, dalam sebuah status kawan saya menceritakan bagaimana video penyerangan brutal di Masjid Selandia Baru ini dipertontonkan oleh seorang guru pada murid-muridnya, sehingga pada akhirnya telah membangun pola pikir pada siswa-siswinya, bahwa semua orang yang bukan Muslim adalah jahat, bejat dan layak dibenci bahkan di perangi.
Teror kebencian itulah yang selalu ingin dibangun oleh seseorang yang selalu merasa terancam. Sehingga dengan serta merta akan menihilkan kebaikan, karena dengan kebencian, seseorang tidak akan sedikit pun mampu melihat kebaikan orang lain. Dan patut disayangkan jika energi kebencian ini telah menyeruak masuk merusak mental anak didik generasi kita, yang semestinya mereka diajari untuk bisa menghargai perbedaan sehingga memudahkan mereka dalam berkolaborasi dan bekerja sama dalam kompetisi dunia yang semakin heterogen.
Di sisi lain, media telah memainkan peran yang sangat strategis saat ini. Media baru, baik itu saluran media mainstream maupun sosial media telah memberikan dampak yang sangat krusial dalam pembangunan karakter publik. Beberapa media telah lebih banyak menekankan sebagai sarana komodifikasi berita ketimbang sebagai saluran informatif yang turut serta membantu menjaga kohesi sosial.
Beragamnya saluran komunikasi dan semakin mudah dan terbukanya akses pengetahuan yang luas dan kompleks, tidak semakin menjadikan masyarakat dewasa dalam menelaah suatu kejadian atau peristiwa. Namun justru seiring semakin meningkatkan kepercayaan diri, menjadikan masyarakat hanya mempercayai terbatas pada apa yang dipercayainya, apa yang diaksesnya, dan bukan berdasarkan dari berbagai fakta dan sudut pandang yang berbeda.
Secara tidak langsung media telah menjadikan masyarakat hanya sebagai konsumen pasif berita-berita bombastis yang tidak jarang justru menggiring opini dalam membentuk kultur kebencian kepada komunitas yang berbeda. Peristiwa ini tentu menjadi perenungan bersama bahwa ‘connecting people’ itu bukan semata menjadikan konektifitas digital ini laksana desa global, tetapi yang lebih penting bagaimana membangun budaya bersama dalam lingkup penghargaan terhadap perbedaan yang menjadi unsur alami, yang senantiasa ada dalam masyarakat dan pada komunitas mana pun.
Hal itu tentu saja tidak cukup dibatasi dalam forum-forum ‘like-minded people’, tetapi diperlukan gairah empati kesadaran bersama bagi semua pemangku sektor publik, maupun tokoh masyarakat dan juga tokoh agama untuk bersama membuka diri pada keniscayaan perbedaan. Selanjutnya perlindungan dan jaminan pada kelompok-kelompok marginal maupun minoritas sudah saatnya menjadi agenda bersama, menjadikan kelompok-kelompok minoritas ini menjadi bagian integral di sekitar kita.
Perlindungan itu menjadi sebentuk pengakuan ‘welcome gesture’ yang akan selalu diharapkan oleh kelompok minoritas, sehingga ikatan komunitas itu dapat terbagun secara kultural dan bukan semata karena faktor rekayasa sosial. Hal ini tentu sangat diperlukan untuk meminimalisir munculnya gerakan ultra-konservatif yang bermuara dari ketidakberdayaan dan tidak terakomodirnya kelompok-kelompok marginal ini dalam mendapatkan haknya sebagai sesama warga negara.
Ketiga, di era di mana media merupakan pisau tajam dan era di mana setiap orang dapat merebut ruang publik digital, sudah saatnya kesadaran literasi media menjadi agenda utama yang sangat diperlukan sebagai gerak bersama untuk bersama membangun kohesi sosial dan membangun kesadaran publik bahwa tidak semua apa yang didapatkan dalam genggaman ponsel, dapat kita bagikan begitu saja, sebelum memikirkan dampak dari apa yang kita bagikan tersebut.
Hanya dengan cara membuka hati, membuka mata dan membangun kesadaran publik maka kedewasaan dalam bermedia dapat terbangun. Kita tentu berharap arus budaya kebencian sebagaimana yang terjadi di Selandia Baru tidak sampai berdampak sosial pada masyarakat kita. Namun setidaknya perlu menjadi antisipasi bersama bahwa kebencian dalam bentuk apapun tidak akan membawa kebaikan bagi siapa pun.
*) Dosen Pengembangan Masyarakat Islam Institut Pesantren Mathaliul Falah (IPMAFA) Pati, Jateng, KAICIID Network for Interfaith and Intercultural Dialogue dan Board Team Indonesia Peace-building Institute.
Sumber: Republika.co.id